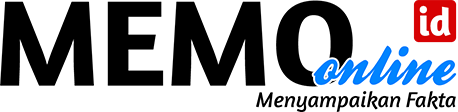Foto: Yunanto mantan wartawan harian sore "Surabaya Post" (1982 - 2002)
Foto: Yunanto mantan wartawan harian sore "Surabaya Post" (1982 - 2002)
Debat Capres Berbahasa Inggris? Banggalah Berbahasa Indonesia
 Foto: Yunanto mantan wartawan harian sore "Surabaya Post" (1982 - 2002)
Foto: Yunanto mantan wartawan harian sore "Surabaya Post" (1982 - 2002)
Oleh: Yunanto.
MEMOonline.co.id - Menjelang akhir pekan ini muncul gagasan debat capres berbahasa Inggris. Argumentasinya, sosok presiden Indonesia harus piawai berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dalam pergaulan internasional dengan bangsa-bangsa di negara lain.
Saya terpana sejenak setelah mengetahui gagasan itu lewat warta di media audio visual (televisi). Saya terpana bukan karena saya pro-bacawapres Joko Widodo, atau saya kontra-bacawapres Prabowo Subiyanto.
Sungguh, saya bukan politisi. Bukan pula anggota partai pilitik mana pun. Predikat saya hanya rakyat, warga negara Indonesia, dan pemegang hak pilih dalam even pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif (pilkada dan pilpres). Soal saya memilih siapa, itu hak prerogatif saya di dalam bilik suara, di TPS.
Saya terpana pada gagasan itu tentu ada landasan argumentasi. Pertama, argumentasi yuridis. Konstitusi negara ini, UUD 1945, telah mengamanatkan bahwa "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia" (Pasal 36). Landasan yuridis berikutnya, tidak ada satu pasal pun di dalam UU No.7/Tahun 2017 ttg Pemilu dan di dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 20/2018 yang mensyaratkan debat capres berbahasa Inggris.
Sedangkan landasan non-yuridis, terkait dengan nasionalisme dan kemanfaatan komunikasi itu sendiri.
Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, jiwa dan semangat nasionalisme harus ada di setiap warga negara Republik Indonesia. Tanpa nasionalisme yang kokoh, seperti telah ditunjukkan oleh para pendahulu lewat "Sumpah Pemuda" 1928, bahaya bagi negara sebesar NKRI. Salah satu wujud konkret dari nasionalisme itu adalah rasa bangga berbahasa Indonesia.
Sejujurnya, almarhum Soeharto, Presiden RI kedua, patut dibanggakan dalam kontek kebanggaannya berbahasa Indonesia. Hal tersebut terlepas dari kualitas demokrasi pada masa pemerintahannya. Terlepas pula dari idioleknya setiap mengucapkan akhiran "kan" menjadi "ken". Satu hal yang membanggakan, Pak Harto pada zamannya selalu berpidato dalam bahasa Indonesia. Di luar negeri sekalipun.
Argumentasinya rasional dan tepat. Intinya, jika bangsa-bangsa mancanegara ingin mengerti isi pidato Presiden Soeharto, kala itu, maka belajarlah bahasa Indonesia. Argumentasi itu sekaligus jadi pemicu semangat menginternasionalkan bahasa Indonesia. Sebuah obsesi yang patut dibanggakan. Menyejajarkan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing internasional (bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa China).
Berikutnya, dari aspek kemanfaatan komunikasi. Kajiannya tentu tidak bisa lepas dari disiplin ilmu Publisistik Praktika. Galibnya, seorang komunikator yang baik wajib berorientasi kepada komunikannya atau khalayak audiennya. Bila mayoritas komunikan tidak bisa berbahasa Inggris, namun komunikator memaksakan diri berkomunikasi dengan berbahasa Inggris, maka dia jelas komunikator tolol.
Ya, tolol, karena isi komunikasinya tidak bermanfaat bagi komunikannya. Bagaimana bisa bermanfaat jika tidak dimengerti? Demikian pula bila terjadi dalam debat capres; terlebih ditayangkan secara luas oleh media audio visual ke seluruh pelosok negeri. Ampun... mayoritas WNI tidak bisa berbahasa Inggris, Bung!
Bertolak dari argumentasi tersebut, tentu saya tidak sependapat dengan pihak-pihak yang empunya gagasan debat capres berbahasa Inggris. Di sisi lain, saya sadar bahwa saya bukan siapa-siapa dan tidak menjadi apa-apa. Maka ketidaksetujuan saya tersebut tidak ada pengaruh sedikit pun terhadap pihak yang "ngeyel" debat capres berbahasa Inggris.
Fakta di pelupuk mata. Bangsa besar di negara Amerika Serikat, tidak punya bahasa Amerika sebagai bahasa persatuannya. Negara besar Australia, tidak memiliki bahasa Australia sebagai bahasa nasionalnya.
Namun, bangsa Indonesia memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, bahasa nasional, sekaligus bahasa persatuan.
Maka, tidak ada alasan bagi seorang pun WNI yang tidak berkenan membanggakan bahasa nasionalnya. Hal itu salah satu wujud nyata dari nasionalisme.
Jadi, di mana pun WNI berada, banggalah berbahasa Indonesia. ( ☆ )
Catatan:
Yunanto adalah wartawan harian sore "Surabaya Post" (1982 - 2002). Alumni Sekolah Tinggi Publisistik-Jakarta. Sekarang bergiat sebagai editor naskah buku dan instruktur diklat jurnalistik.