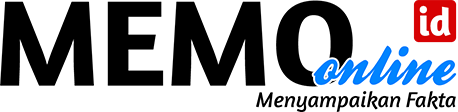Foto: Maliatuz Zahroh, Tim Redaksi MEMO online
Foto: Maliatuz Zahroh, Tim Redaksi MEMO online
Malangnya Sukri dan Wanita Penjual Ikan
 Foto: Maliatuz Zahroh, Tim Redaksi MEMO online
Foto: Maliatuz Zahroh, Tim Redaksi MEMO online
Oleh: Maliatuz Zahroh
MEMOonline.co.id - Nopember yang basah, Ambunten Timur Sumenep
Abantal angin asapo’ ombak
Abantal syahadat asapo’ angin apajung Allah
Frasa itu sering diucapkan Lastri kala senja bertandang. Bau mulut yang beraroma jengkol tak pernah membuat anak-anaknya enggan mendengarkan petuah-petuahnya. Entah Ia mengutip dari buku apa. Rasanya seperti mendengar roda buldoser berdentam-dentam keluar dari liang neraka . Menyayat perih setiap kali teringat suami yang pulang sebulan sekali, terluntang-lantung di tengah laut. Bersahabat dengan badai, ombak dan rasa takut.
Seperti senja ini
seperti senja-senja yang lalu
dan seperti senja-senja berikutnya
Pemandangan sore itu jauh dari kesan indah, dengan pemandangan laut biru sekalipun. Apalagi sekadar duduk di pinggir pantai yang mencekam. Menunggu kapal-kapal itu menepi, menunggu janji-janji itu terlunasi. Gelap. Petir sesekali menyambar, menggelegar memperburuk keadaan.
Lastri berdiri cemas di bibir pantai. Kakinya yang tak bersandal seperti sudah kebal pada tusukan kerang dan batu karang. Matanya lekat menatap laut lepas yang berombak. Siapa yang tahu, suasana hatinya jauh lebih buruk dari segala badai sore itu.
“Mole gellu, Kak. Langnge’ petteng. Pera’ tadhe’ pesse aotang gellu,” teriak Lastri berkali-kali. Tak peduli seberapa parau suaranya. Sesekali Lastri mengusap ujung matanya yang basah, membayangkan wajah lelah lelaki yang selama ini menafkahi dirinya lahir batin.
Batin? Sepertinya sudah tidak lagi sejak nyaris seluruh waktu suaminya di habiskan di tengah lautan, disamping karena usia mereka yang sudah tua dan beranak dua.
Lastri masih mematung, mengabaikan perutnya yang keroncongan minta diisi. Rambut yang sedikit memutih sesekali diterpa angin menghalangi pandangan matanya. Ia tiba-tiba teringat kedua anaknya di rumah. Betapa mereka pasti ketakutan tanpa ditemani seorang ibu di cuaca seburuk ini.
Seberkas harapan muncul ketika matanya yang sembab menangkap sebentuk sampan yang semakin mendekat. Jelas terlihat nelayan itu dengan tergesa mendayung kearah tepian. Wajahnya yang panik tergambar jelas saat ombak membuat oleng sampan berwarna kuning gading miliknya.
“Nyare mate manjheng e jeriya, calemotan dheri bere’, topan marena deteng,” teriak seorang lelaki yang Ia duga suaminya. Seulas senyum yang tersungging hilang seketika.
Lelaki tadi bergegas mengambil barang-barang miliknya, tak terkecuali hasil tangkapan ikan yang hanya setengah karung kecil. Dengan masih menatap bingung kearah wanita itu, ia lantas berlari tanpa sandal.
*
Ngapote wa’ lajere etangale
Reng majhang tantona la padhe mule
Du mun ecelling odhi’na oreng majengan
Apental ombek sapo’ angin salanjenga
Ole olang paraona alajere
Ole olang alajere ka Madhura
Lagu itu terdengar lirih. Samar-samar dilantunkan Lastri dengan mata berkaca-kaca. Debur ombak semakin terdengar menakutkan. Petir menyambar tak kalah sangar. Di tengah cuaca seburuk itu, suaranya seperti sedang melantunkan kidung kematian. Ada luka yang bahkan tidak bisa ia jelaskan lewat ucapan.
Ngapote wa’ lajere etangale
Reng majang tantona la pade mole
Berulang-ulang lagu itu dilantunkan. Ia sedang menghibur diri. Berharap dua baris lagu itu akan dikabulkan Tuhan, secepatnya.
“Buk,” suara itu. Suara yang nyaris terdengar bersamaan di telinganya. Wanita itu menoleh dan mendapati kedua anak lelaki berlari mengahambur ke pangkuannya. Ia memejamkan mata. Tangannya yang dingin merengkuh kedua putranya erat. Sekadar menekan gemuruh di dadanya yang membuat sesak. Dalam hati ia berdoa, manteren tak andi’e kalakoan enga’ bapakna se lako maseal ka reng budih .
Azan maghrib telah berkumandang lima belas menit yang lalu. Mereka masih mematung memandangi laut lepas. Gelap. Hanya ada sedikit penerangan dari senter geretan di tangan anak bungsunya.
Allahumma Shalli’ala Muhammad, Shallallah ‘alaih...
Suara shalawat itu berasal dari rumah tetangganya yang bernama Busri. Seharusnya Ia berada di sana bersama anak dan suaminya. Bersalawat khidmat dengan para tetangga yang lain.
Si bungsu merengek di lengan kirinya. Sang Ibu hanya menatap miris pada buah hatinya yang sesekali menggigil kedinginan, sedang putra sulung yang memegang tangan kanannya seperti sedang menguatkan, mengerti. Pelan mulutnya bergumam lirih “Bapak.”
###
Sukri’s POV
Selembar bulu matamu yang lepas dan jatuh ke bumi
Suaranya berdentum
Kukira ia tak rela meninggalkanmu
Ternyata dentuman tadi hanya sejenis pengumuman tentang
Indahnya kebebasan .
Suara-suara sapi itu terdengar bising di telinga. Membuat kantukku lenyap seketika. Mataku menerawang seluruh isi ruangan, tepat pada kalender yang tergantung di dinding aku menyadari sesuatu yang berada di dalam lingkaran warna merah.
Tanggal 11 Desember, besok, adalah kerapan sapi yang akan berlangsung di Lapangan Sepakat Sumenep. Bergegas aku ke dapur, mengambil ramuan konce, bawang, membuat santan dan gula siwalan untuk jamuan Rimba-sapi jantan yang selalu membuatku bangga.
“Jadi yang mau lomba kerapan sapi besok, Pak?” tanya istriku seraya menyerahkan secangkir kopi dan semangkok singkong rebus.
“Tentu saja, Mar.”
“Sudah sesuai dengan perhitungan pancabara?” Tanyanya lagi.
“Sudah, Mar,” jawabku tanpa memalingkan muka.
“Itu buat apa, Pak?” kejarnya melihatku sedang meracik sesuatu. Ah, istriku sekarang jadi semakin cerewet. Aku baru ingat saat sebulan yang lalu dia mengintrogasiku habis-habisan karena melihatku dengan wanita itu.
Wanita yang berdiri cemas di pinggir pantai. Iya, wanita itu, dengan dua anak yang selalu bergelayut manja di dua lengannya. Aku hanya tidak sengaja menyapanya. Aku hanya tidak sengaja bercakap panjang lebar dengannya. Mirisnya, akupun tak sengaja jatuh hati padanya.
“Jamuan si Rimba, biar larinya ringan, cepat dan kuat.”
“Ohh.”
Selesai ber-oh panjang, Martini masuk dengan muka ditekuk. Aku bernafas lega tanpa perlu lagi menjawab pertanyaan basa-basinya. Aku jadi teringat moment di pantai itu.
“Bapak,” telingaku menangkap putra sulungnya bergumam lirih. Pelan-pelan aku mendekat dan menegurnya.
“Akan turun hujan, bergegaslah bawa anak-anakmu pulang,” kedengarannya sok akrab memang tanpa sebelumnya kenal. Dia menoleh, dengan seulas senyum dia merespon ucapanku.
“Saya sedang menunggu suami.”
Suaranya serak dan parau. Matanya sembab sedikit memerah. Jelas sekali dia baru saja menangis menunggu kepulangan suami tercinta. Aku hanya mengangguk dan berlalu pergi. (*)
*Maliatuz Zahroh, salah satu Tim Redaksi MEMO online sekaligus anggota Forum Lingkar Pena Cabang Sumenep.